
Aku benci !!! Aku benci menerima surat itu lagi. Muak. Kenapa mereka tidak pernah mau mengerti. Aku butuh ketenangan di sini. Kalau bukan surat yang mengabarkan ayah sedang sakit-sakitan, maka isinya pasti tentang adik-adikku yang merasa kekurangan uang sekolah dan jajan mereka. Lebih menyakitkan lagi, ibu dengan tangis setiap malam memanggil aku pulang. Tidak. Aku tidak akan pulang. Kemarin. Surat itu datang.
27 Ramadan 1424 H.
Ramadan, cucuku… Nenek merindukan kamu. Empat Ramadan berlalu, dan kamu tak pernah punya niat ke kampung. Mekipun hanya sesaat. Kami tahu, betapa sakit hatimu pada ayah dan ibumu. Mereka sudah tak lagi murka. Sekejam-kejamnya mereka, kesedihan selalu merundungnya. Tahukah kamu, setiap Ramadan tiba, ibumu tidak pernah berhenti menangis. Apalagi ketika malam dua puluh delapan Ramadan tiba, saat engkau dilahirkan. Ibumu tak pernah tidur. Entah, mungkin besok dia akan menyiksa dirinya lagi. Ram, sejak tahun ketiga kepergianmu dari rumah, ayah dan ibumu sudah memaafkanmu. Dia ikhlas menerima perempuan pilihanmu. Bawalah istrimu serta, ketika kau sudah berniat ingin pulang. Tolong kau jelaskan baik-baik pada istrimu, keluarga kita akan menerimanya dengan tulus. Lupakanlah masa lalumu dan kemurkaan ayahmu ketika itu. Ingat, kini ayahmu tak bisa bekerja lagi. Adik-adikmu ingin sekolah dan butuh belanja. Sementara keluarga yang lain, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kakak ibumu tak pernah lagi berkunjung ke sini, ketika tahu kau dilarang pulang ke rumah. Ram, nenek mengerti, kenapa setiap nenek menulis surat untukmu, tak pernah sekalipun kamu balas. Tak apalah. Tapi nenek harap, surat ini tidak menunggu balasanmu. Melainkan kedatanganmu. Ingat itu. Apakah kamu tidak pernah mengerti perasaan nenek. Ingin sekali rasanya memelukmu, membelai rambutmu, dan mendengar cerita-ceritamu seperti dulu setiap kau kembali liburan kerja. Tapi kini… semua jadi sepi. Sekali lagi pulanglah, Ram. Tunaikanlah panggilan orangtuamu. Dan kesempatan inilah kamu bisa menunjukkan baktimu pada keluarga. Sekali saja. Nenek mohon… Nenenda.
Tidak. Jangan menangis Ram. Bisikku pada hati yang hampir luluh. Aku tidak akan pernah pulang. Sekali terlarang menginjakkan kaki di kampung halaman. Selamanya tidak akan pernah. Itulah kekuatan hati, yang membuat aku bertahan hidup di kota ini bersama istriku. Disamping ketabahannya. Maaf Nek, aku juga merindukanmu. Andai saja ayah dan ibu tak ada di sana. Tanpa nenek mintapun, aku akan pulang. Tapi selama mereka masih ada di sana, aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pernah pulang. Selama mereka tidak meminta maaf atas kesalahan mereka. Bukan aku yang dimaafkan. Sebab aku tak pernah merasa bersalah. Merekalah yang tidak pernah mau mengerti perasaanku. Pagi-pagi sekali, di atas meja teras depan, sebuah surat bersampul putih dalam kondisi seperti sudah dibuka ada di sana. Entah siapa yang membukanya. Istriku? Aku membukanya…
28 Ramadan 1424 H
Untuk Ramadan,
cucuku… Ram, nenek sudah tidak tahan melihat penderitaan ibumu. Tangisnya menjadi-jadi. Setiap dia menyebut namamu, dia berteriak hingga suaranya parau. Dan kesedihan yang paling tak bisa nenek tahan, dia seperti lupa kepada semuanya, kecuali kamu cucuku. Ibumu sudah beberapa hari ini tak bisa puasa, karena menangis meraung-raung terus. Ayahmu, malam tadi, hampir tak tertolong. Nafasnya tak bisa ia kendalikan, terengah-engah setiap kali mendengar ibumu meraung-raung. Kami khawatir, jantungnya kambuh lagi. Adik-adikmu tak bisa berbuat apa-apa, hanya bingung dan bingung. Kami ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi tak mungkin. Kamu tahu kan, selain ayahmu, tak ada lagi penopang belanja keluarga. Tabungannya sudah habis untuk beli obat. Kami hanya menunggu kehadiranmu. Hanya itu. Mungkin setelah melihatmu, akan ada perubahan. Ram, sadarlah… kebencian apapun pada orangtuamu, kembali dan maafkanlah dia, kalau memang kesalahan ada pada mereka. Sekeras apa pun batu, kalau ia ditetesi air akan berlubang juga. Ingat, cucuku. Bulan ini adalah bulan milikmu. Ramadan, ingatkan dengan nama itu. Kamu harapan nenek satu-satunya. Dan detik terakhir inilah kita bisa saling memaafkan selama empat Ramadan berlalu. Sekali lagi, cucuku, sebelum datang murka Allah padamu, maka datanglah bersujud pada ibu dan ayahmu. Murka Allah tergantung pada murka ayah dan ibu. Restu Allah tergantung restu ayah dan ibu. Yakinlah cucuku, ketika hatimu terbuka, maka akan banyak pintu Allah yang akan dibukakan untukmu.
Nenenda
Dari balik punggungku. Seorang perempuan dengan jilbab yang rapi telah berdiri disana. Istriku. Ia menatapku kosong dan kecewa. Sebening air jatuh dari bola matanya. Terisak. Sedih. Dia tak mengatakan apapun. Dia terus menggelengkan kepala. Sepertinya ia tak menerima sikapku selama ini terhadap ayah dan ibu. Aku mengerti. Dia sudah tahu semuanya.
“Dik…” ia menatapku lebih dalam. Tertunduk. Tangannya terangkat.
“Cukup, Kak, tidak ada yang perlu dijelaskan. Dan tidak ada alasan untuk tidak kembali melihat ayah dan ibu.”
“Baiklah, bagi kamu mungkin, tapi bagiku, ada seribu alasan untuk itu, aku tidak akan pulang.”
“Kak, sekeras itukah hatimu, Allah saja memaafkan hamba-Nya. Apalagi kakak. Ingat, Kak, mereka adalah nadi kita. Tanpa mereka kakak tidak akan pernah ada. Dan tidak akan sesukses saat ini. Istighfar, Kak. Jangan durhaka.”
“Pahamilah aku, Istriku. Saat ini aku tak bisa. Aku tidak mengijinkan dan tidak melarang adik berkunjung pada mereka. Tapi kalau ingin, itu adalah keputusan adik sendiri. Aku akan pulang sampai saat itu tiba.” jelasku. Istriku memutuskan pulang. Maaf dik. Aku tak bisa memenuhi panggilan mereka. Hati ini terlalu sakit. Setiap aku mengingat kata-kata mereka, setiap itu pula, hatiku seakan teriris.
“Istriku, satu pesanku. Ketika sampai, tolong jangan katakan apapun tentang aku. Mereka hanya perlu tahu, aku tidak akan berubah. Dan jangan meminta aku datang dengan alasan atas namamu. Aku tidak akan lakukan. Pergilah sayang, salam pada nenek tercinta, Assalamu Alaikum.” tegasku.
“Wa Alaikumu Salam.” jawabnya sambil mencium tanganku. Malam takbiran. Aku sendiri. Suara takbiran berkumandang dari sudut kota. Suara itu mengalunkan kebesaran Allah SWT. Pawai keliling dengan kendaraan mobil dan motor tak ketinggalan, semakin menambah semarak malam lebaran. Tapi, malam ini, aku gelisah memikirkan istriku. Aku seperti terasing di rumah sendiri. Akh, mungkin hanya perasaanku saja. Baru kali ini, aku ditinggal pergi istriku sejak pernikahan kami. Jadi aku pikir wajar kalau mengkhawatirkannya. Sesaat, telepon berdering.
”Assalamu Alaikum.” Okh istriku. Suaranya parau.
“Wa Alaiku….. Minal Aidin Wal ….,” suaraku terpotong olehnya.
“Cukup, Kak. Dinda memaafkan Kakak bila pulang malam ini. Waktu itu telah tiba. Ayah telah pergi dan ibu…..”
“Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Raaji’un.”

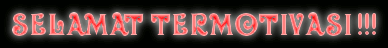
Tidak ada komentar:
Posting Komentar