
Malino, Indonesia. Villa di sebuah desa. Pukul 02.00 dini hari. 2007
Udara dingin terasa semakin menusuk tulang belulang. Entah suhu berapa. Kurapatkan kerah jaket bulu agar suhu badanku bisa seimbang dengan suhu udara di luar sana. Kedua tangan kulipat dan kurapatkan di dada. Kaki yang terbungkus dengan kaos kaki tebal, kuangkat ke atas sofa, agar merapat dengan kedua paha. Tapi udara dingin di luar lebih menusuk dibanding usahaku menghangatkan diri. Sejatinya, Malino bukanlah tempat yang cocok buatku menunggu kedatangan Kekhan. Namun, atas permintaannya, aku terpaksa menutupi rasa sesak di dada setiap mendapatkan udara dingin. Bronkhitis yang aku idap sejak kecil menjadikan aku tersiksa jika berada di ruangan dingin, apalagi di udara bebas. Tapi demi Kekhan, aku rela. “Ode, kamu tunggu aku yah di Villa sampai aku datang. Kita bisa menikmati cinta sepanjang malam di sana. Berhentilah berkelana. Kamu jadi penulis saja di villa kita”. Begitu Kekhan melirih, saat kami berpisah di Malaysia tiga tahun lalu.Tempat ini adalah villa milik Kekhan yang sengaja dibuatkan Ayahnya. Ayah Kekhan lebih memilih berdomisili di kota kecil di Austria. Kekhan sangat senang dengan udara pedesaan dan pegunungan yang di kelilingi kabut tiada henti. Malino telah memikat hatinya. Sesak semakin menghimpit dadaku. Batuk-batuk kering disertai sedikit lendir, mulai hadir lagi. Akh untuk kesekian kalinya, aku harus membiarkannya.Hari ini adalah hari ketiga aku menunggu kedatangan Kekhan. Kekhan mengabari akan datang sebelum perayaan ulang tahunnya yang ke 28 tahun. Tapi entah kenapa dia belum datang juga. Maksud hati ingin menelpon ke Hp-nya, tapi ia melarang. Katanya ingin memberikan surprise.
Bali, Indonesia. Januari 1999.
Tugas dari kantor membuat tulisan khusus tentang kehidupan masyarakat Bali membuat aku semangat melepas semua permasalahan hidup di Kota Makassar. Hari ke tiga tiba di Jimbaran, membuatku semakin melupakan kemelut perceraian orang tuaku. Sari Segara Resort, tempat menginap membuatku nyaman berlama-lama. Suatu sore menjelang senja. Jimbaran Café begitu ramai oleh bule yang sedang menikmati bir dan vodka. Aku duduk menikmati senja, sehabis keliling di pemukiman sekitar Jimbaran. Rasa lelahku sirna saat menikmati alam yang senja. Setengah jam melamun, seorang laki-laki tegap mendekatiku.“Kenalkan, Brana. Boleh saya duduk?”, sapanya akrab dengan dialek campuran Manado dan Melayu. Ia duduk meski belum aku persilahkan. Aku tersenyum sambil menawarkannya minum.
“Maaf? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?”.
“Belum!”
“Terus?”, tanyaku sedikit heran.
“Sedari tadi saya mengamati Anda, dan sepertinya saya sangat ingin mengenal Anda”.
“Oh ya?”, kali ini saya sedikit bergumam.
“Yap, sangat ingin!”, ia tersenyum mantap.Tidak lebih satu jam, kami sudah saling mengenal. Ia banyak bercerita tentang masa-masa kecilnya di Manado. Masa-masa remajanya yang suram. Hingga kehidupannya yang mendapat tantangan dari keluarganya. Ia juga bercerita, kenapa ia memilih menetap di Bali.
“Di sini aku bisa bebas menentukan hidup, Ode. Hidup denga siapa saja, tanpa ada yang mengekang. Aku bebas. Bali memberikan segalanya”, tandasnya sambil tersenyum hangat.Kami bertukar pikiran tentang kehidupan. Brana memberikan banyak inspirasi soal hidup. Khususnya terkait dengan masalah orang tuaku saat ini. Aku kagum padanya, entah rasa kagum itu seperti apa. Sorot matanya tajam dan memukau. Aku begitu tertarik padanya.Pertemuan dengan Brana semakin sering terjadi. Ia selalu punya banyak waktu buatku. Apalagi menjelang senja di Jimbaran Café. Kami menghabiskan waktu hingga malam, hanya sekadar minum-minum. Atau hanya diam saling menatap dengan dalam. Suatu hari aku mengajak ia ke resort. Menghabiskan malam bersama Brana. Sepanjang malam, larut dalam buaian angin Jimbaran. Cinta berpantang pun kami arungi. Kami bebas dan hanyut. Kami ternyata saling membutuhkan dan merindu setiap saat. Akh…, Brana sudah menjadi bagian hidupku yang begitu berarti. Akhir tahun 2002 lalu, kami putus kontak sejak Bom Bali meledak. Entah Brana berada di mana. Ia juga tidak pernah memberikan kabar. Ingin rasanya aku ditugaskan kembali menulis tentang kehidupan masyarakat Bali pasca Bom Bali tersebut. Sayang, aku ditugaskan di Papua hingga tahun 2003. Setelah itu redaksi menugaskan aku ke Pulau Mindanau, Filipina. Hingga tahun 2004, aku ditugaskan ke Sandakan, Malaysia.
Perkebunan Taiko Platation, Sandakan, Malaysia. 2004.
Kehidupan masyarakat bugis di perantauan, khususnya bagi mereka yang bekerja di perkebunan mengingatkan aku pada Brana. Perjuangan mereka yang gigih mengenangkan usaha Brana bengkitkan aku dari kemelut. Aku berada di Sandakan selama tiga bulan untuk mengumpulkan data-data tentang kehidupan suku Bugis Makassar di negeri Jiran. Ternyata, di lokasi perkebunan Taiko Platation (dulu bernama Borneon Estate Sdn Bhd), juga terdapat seorang mahasiswi dari University of Malaya yang melakukan penelitian Antropologi. Namanya Kekhan. Berasal dari Kota Watampone, sebuah kota di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kekhan studi S2 di Malaysia mengambil jurusan Antropologi. Ternyata ia juga tertarik dengan kehidupan masyarakat bugis, yang akan dijadikannya sebagai tesis.
“Kekhan, from South Sulawesi, Indonesia!”, katanya mantap saat kami bertemu di kantor Taiko. Aku pun menyebutkan nama dan tempat asalku bekerja. Ia terkejut.
“Wow, saya suka membaca koran Anda”, ia lalu membuka diri dan bercerita banyak tentang dirinya selama studi di Malaysia. Ternyata Kekhan adalah anak pengusaha tersohor di Makassar. Usaha ekspor impor rumput laut ayahnya begitu maju. Kehidupannya begitu terjamin. Ia nyaris tidak bertemu dengan ayahnya dalam dua tahun terakhir, karena ayahnya memilih tinggal di Austria.Di sela-sela melaksanakan tugas jurnalistik, aku banyak membantu Kekhan mengumpulkan data dan wawancara. Hampir setiap hari kami bersama. Mess yang diberikan kepada kami memang tidak begitu jauh. Hanya satu blok. Kadang aku nginap di Messnya, kadang ia pun tidur di Messku. Brana sedikit terlupakan. Jujur, baru kali ini aku akrab dengan wanita. Aku terlalu sibuk melanglang-buana dari daerah satu ke daerah lain. Dari negara satu ke negara lain, hingga melupakan sosok wanita. Laki-laki jauh lebih berarti dan berkesan. Entah, aura Kekhan menyadarkan aku pentingnya seorang wanita. Ternyata kelembutan Kekhan mengalahkan Brana yang pernah memberikan cinta selangit. Dua bulan lebih bersama, kami memilih mengikrar hati. Aku memberikan sebuah cincin manis di jarinya dan selembar kain biru yang kusobek dari lengan kemejaku.
“Kekhan, simpan yah, sampai kita bertemu di Indonesia”. Ia mengangguk.
“Aku akan pulang mungkin setelah yudisium dan mendapatkan ijazah“. Ia terdiam sejenak.
”Ode, ingatlah malam-malam kita di sini jika engkau rindu, dan kuharap kamu tidak lagi berkelana. Berjanjilah menemani malam-malamku di simpang satu itu“. Ada setitik air yang tak jadi keluar dari sudut matanya. Ia menyerahkan amplop tebal sebelum berpaling.
Bandara Hasanuddin, Makassar. Indonesia. Akhir 2004.
Di luar bandara sambil menunggu taxi bandara yang akan mengantar aku ke rumah, kumembuka amplop pemberian Kekhan. Ternyata surat singkat yang bertuliskan, “Tinggallah di dalamnya, dan tunggulah aku. Kita ciptakan malam-malam yang lebih indah nanti“. Ada pula selembar surat kuasa pemakaian villa yang ditujukan padaku, lengkap dengan alamatnya. Sebuah kunci, yang aku pastikan kunci villa milik Kekhan. Kekhan… Kekhan… kamu begitu baik, gumamku dalam hati. Aku bergegas pulang setelah ada sopir taxi memanggil. Satu tahun kemudian aku putuskan berhenti jadi wartawan dan menjadi penulis lepas. Aku menulis novel tentang kehidupan masyarakat yang pernah aku kunjungi saat bertugas menjadi jurnalis. Sejak awal 2006 aku berdiam di villa milik Kekhan. Menunggunya segara datang di ujung jalan buntu, di simpang satu. Aku selalu bermimpi tentang malam-malam indah yang akan kami arungi. Tapi setiap aku bangun, hari masih dini hari. Kuhanya mendapatkan udara dingin dan tiupan angin, menusuk dari sela-sela jendela yang selalu aku biarkan terbuka.
Malino, Indonesia. Villa. Pukul 05.00 subuh. 2007
Suara pukulan pagar berkali-kali membuyarkan lamunanku tentang Kekhan. Ada suara kecil dan lembut memanggil namaku. Kekhan!!! Itu pasti Kekhan. Aku sontak berdiri. Udara dingin subuh yang menusuk dada dan batuk keringku tak kuhiraukan. Aku menyambanginya segera. Mimpi tentang malam-malam indah kami akan terwujud. Pasti.Belum tiba di pagar, tiba-tiba di depanku berdiri sosok yang selama ini telah aku lupakan.
“Brana, kenapa kamu yang datang?” Aku tambah shock ketika melihat di tangan Brana ada sepotong kain dari kemejaku, dan… dan… cincin tunangan kami ada di jari manisnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku berteriak sekeras mungkin.
“Brana, Kekhan di mana?”, ku genggam kerah bajunya dan mengangkat setinggi mungkin.
“Kamu apakan Kekhan, hah!”. Ada senyum di bibir Brana. Tak dihiraukan amarahku. Tanganku disentuhnya dengan lembut, dibelainya dengan mesra. Cincin tunangan dijari manisnya disentuhkan ke wajahku. Dikecupnya keningku. Amarahku semakin memuncak sampai ke ubun-ubun.“Brana, hentikan!” Tapi, tangan Brana semakin liar dan kuat. Aku meronta-ronta. Tubunya kudorong sekuat tenaga. Sontak dari balik bajunya ada logam tajam jatuh ke lantai. Ada tetesan darah di situ dan beberapa helai rambut.
“Akh, Kekhan …. Kamu biadab, Brana!” Brana tertawa terbahak-bahak.
“Akulah yang kamu tunggu, Ode“.

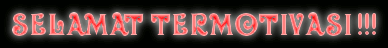
Tidak ada komentar:
Posting Komentar